MALAPETAKA: Malah Pengen Tambah, ‘Kan?
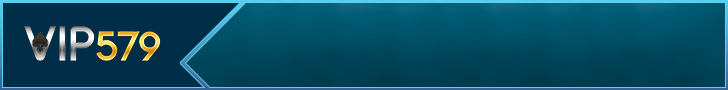
.gif)





Tertanda,
S. Etan
***
a fatal dickcision
Egi mondar-mandir di ruang tamu mungil itu. Sengaja dia hindari tatapan sesosok wanita dalam balutan hijab dan gamis lebar yang tengah duduk pada kursi yang letaknya paling jauh dari pintu. Tatapan yang biasanya teduh itu kini sedang mengulitinya. Sesekali Egi akan mendongak, mengintip dari celah pintu. Derum motor yang dia nanti-nanti belum juga menyambangi ruang dengarnya.
Biji-biji keringat kian memberati dahi, tengkuk, leher, serta ketiaknya. Padahal, dia baru mandi menjelang petang lalu. Lembap udara musim pancaroba tak membantunya meraih tenang. Membantunya menjernihkan pikiran. Sedari awal, dia menentang gagasan yang sekarang tengah dijalankan. Dia yakin masih ada cara lain. Cara yang lebih dia bisa terima. Namun, apa mau dikata. Egi kalah adu argumen. Karakternya yang meledak-ledak tetapi gampang menciut sama sekali tak membantunya.
Dua tahun sebelumnya, Egi akan sulit membayangkan dia berada di posisinya saat ini. Kala itu, dia masih punya pekerjaan tetap. Masih digaji tiap bulan. Masih kadang dapat upah lemburan. Hari ini? Boro-boro. Teknologi yang tadinya dia yakini adalah pintu rezeki, kini merampas hidup dan hampir segala yang dia punya. Ilustrator yang bulan depan menyentuh kepala tiga itu tak habis pikir. Bisa-bisanya dia digantikan kecerdasan buatan alias AI. Kok, ya, ada klien yang mau beli hasil karya dari mesin durjana? Gila. Dunia sudah gila. Dan dia bersama 95% kawan seprofesinya dipaksa ikut gila juga karenanya.
Sebelum hengkang menjual rumahnya di kota untuk lalu pindah ke desa, dia sempat mencoba menjadi ilustrator lepas, yang ternyata lebih sulit dari yang dia kira. Budaya kerja kantoran sudah kadung melekat. Menggantungkan hidup dari freelance, dia putuskan, bukanlah pilihan yang tepat. Ditambah lagi, dia juga depresi dengan kehidupan seksualnya. (More about this later)
“Bi?” panggil si akhwat yang ikut gerah menyaksikan laki-laki yang enam tahun belakangan menjadi suaminya. Kantung gelap di bawah kelopak mata lelahnya membuatnya tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Kecantikan yang dia bawa dari hari-harinya tinggal di kota memudar di luar kuasanya. Menjadi petani, dulunya, dia kira adalah pekerjaan mulia. Bisa bikin orang awet muda. Lepas dari stres ibukota. Bahagia. Sentosa. Pret. Kutukuda! Mau-mau saja dia dibohongi mertuanya—yang seumur-umur lebih banyak main gaple daripada kerja keras sebagaimana semua manusia seharusnya.
Lihat Juga : Foto Bokep Jepang
Bertani itu yang ada malah pusing tujuh keliling. Biaya produksi dan profit sering jauh jomplang. Buruh dan pupuk berlomba-lomba menjadi yang paling langka. Belum lagi dunia yang kian tua ternyata adalah rumah bagi mutasi hama yang bikin garuk-garuk kepala. Jika padi dan palawijanya secara ajaib selamat sampai dipetik, tengkulak masih akan memangsanya.
Konon, ini semua salah pemerintah yang tak becus urus negara. Egi termasuk mereka yang percaya. Gemar betul lelaki itu menyalahkan dunia. Semuanya salah. Kecuali dirinya. Narsis. Egois. Kayak dunia berputar buat dia aja.
“Duduk dulu, Bi. Capek aku nonton Abi mondar-mandir terus.”
“Tapi, Sit,” bantah Egi yang jarang menyebut nama asli istrinya, “ini salah. Keliru. Syirik! Sesat!”
Sita pendam keinginannya untuk tertawa. Sesat? Ide siapa itu cari-cari pertolongan ke ustadz-ustadz dan kiai? Ide Egi. Hanya karena salah satu dari mereka lebih nyentrik dari yang lain, tiba-tiba saja suaminya itu berubah pikiran. Mana telat lagi. Meski jengkel, Sita berusaha menyembunyikannya. Tidak elok suami dan istri bertengkar. Perceraian, lagipula, dibenci tuhan.
Sita menghela napas, lalu mengembuskannya pelan. Dia tahu stress tidak akan banyak membantu keadaan. Hanya saja, susah baginya untuk tak berpikiran ke sana. Hari-hari yang dia jalani bersama Egi menguras tenaganya. Belum lupa dia akan tawaran keluarga besarnya di Surabaya. Meski sempat bersitegang gara-gara dulu dia hijrah, mereka kini bersedia menerimanya kembali. Asal… dia tinggalkan Egi.
Bohong jika wanita berlesung pipit itu tidak pernah memikirkan opsi itu. Terlebih, belakangan ini, dia rasakan Egi semakin berjarak dengannya. Tidak seperti ketika mereka masih Mereka memang masih tidur seranjang. Tetapi—
“Harusnya kita nggak cari bantuan ke… makhluq. Tapi ke Khaliq,” ujar Egi yang baru mulai sembahyang saat ikut rohis kampus. “Ujian ini dari tuhan, Mi. Kita hanya harus kuat menjalan—“
“Iya, dari tuhan, Abi.” Akhwat pemilik nama lengkap Mar’atus Salihatul Masyitah itu terdengar ketus. Taring gingsulnya yang jarang dia tunjukkan kali ini nampak saat dia bicara. “Tapi, ya, harus ada yang namanya usaha. Abi nggak bisa tidur mikirin tumpukan utang. Mikirin kenapa kita sial terus. Ini kita minta bantu orang pintar juga biar kita bisa merem. Biar masih bisa sewa sawah lagi tahun depan. Biar nggak kejual ini rumah. Biar survive. Abi sendiri juga yang awalnya—”
Muka Egi yang merah padam mendongak. Dia punggungi Sita yang tak menyelesaikan kalimatnya. Dari jalan setapak yang tersambung ke jalan utama desa dia dapati sesosok pria berkepala botak dan bermata cekung yang adalah ayahnya berkendara mendekat.
Di belakangnya, sebuah minivan hitam mengikuti. Plat putih kendaraan roda empat itu luar daerah. Memandanginya, Egi terlempar kembali pada pertemuan pertamanya dengan Pak Pak Reksha di kediaman yang bersangkutan di B*J*negoro. Pria itu adalah orang kedelapan yang dia mintai pertolongan. Kepadanya Egi utarakan segala keluh kesahnya. Mulai dari tikus, burung, dan belalang yang silih berganti menyikat sawah; ayam-ayam petelur ayahnya yang mati mendadak tanpa menunjukkan gejala-gejala sakit apa-apa; dia yang celaka didorong tangan tak kasat mata saat motoran sendirian di jalan provinsi dan; hingga gemuruh tapak kaki raksasa yang seakan hendak meruntuhkan atap rumahnya setiap malam menua.
“Mas Egi tenang saja,” ucap Pak Pak Reksha waktu itu. Orangnya gembul serupa bola. Merokoknya pipa. Giginya sedikit lebih maju dari kebanyakan. Sembari memilin-milin jenggot kambingnya dia yakinkan Egi dan Sita agar tidak cemas. Agar mereka segera pulang dan menaburkan tanah merah yang dia berikan pada batas-batas tanah mereka. Niscaya, dengan demikian, gangguan-gangguan yang mereka alami akan sirna. Jika ternyata belum manjur, dia sendiri yang akan datang dan membereskan semuanya. Dan benar saja, dia tepati omongannya usai ajiannya terbukti seberguna kata-kata ‘semuanya akan baik-baik saja’ yang diucapkan setengah hati.
Setelah dipandu Pak Pak Basuki—ayah Egi—sejak dari terminal lama dia tiba juga di rumah yang paling ujung dan cukup jauh dari rumah-rumah tetangga itu.
Hal pertama yang Pak Pak Reksha lakukan ketika dia menginjak tanah pekarangan adalah meludah ke kiri. Dia lalu menengadah pada jejak-jejak senja di barat. Dalam waktu dekat semburatnya akan digilas petang yang membawa mendung. Ragu hujan akan turun, Pak Reksha mengalamatkan pandangannya pada pasangan suami-istri yang jika berdiri bersisian sama tinggi itu dan berkata, “Ini parah, Mas, Mbak.”
Pucat seketika wajah-wajah Egi dan Sita yang menyambut dari teras. Kalau Pak Reksha saja tampak cemas, mereka berdua bisa apa?
“Kerasa, kan, Sir?” tanya Pak Pak Reksha pada sopir sekaligus asistennya yang menyusul turun dari kabin. Di satu tangan, Basir menenteng ayam jago serbalegam dalam kiso rotan dan satu keranjang bunga tabur di tangan yang lain. Sebuah ransel di pundak melengkapi penampilannya yang berpakaian serba hitam sebagaimana bosnya. “Begitu turun, langsung kecium. Mak deg! Bajingan tenan.”
Basir yang berambut ikal gondrong mengangguk tapi tak mengatakan apa-apa. Perawakannya yang tinggi besar menjulang membuatnya seperti sedang salah tempat di antara mereka yang puncak kepalanya hanya sebatas ketiaknya.
Petang itu bukan kali pertama Egi dan Sita berjumpa Basir. Meski demikian, mereka masih merasa kurang nyaman berada di dekatnya. Egi karena dia merasa kerdil di dekatnya. Sementara, Sita karena trauma pernah hampir dilecehkan atasannya yang bule di kantor tempat dia terakhir bekerja sebelum ikut suaminya ke desa.
Dasar lelaki. Padahal Sita selalu berpakaian sopan. Bukan salahnya jika tonjolan payudaranya kadang masih tampak dari luar gamis serta jilbab yang dia kenakan. Pantatnya yang cenderung bulat dan sekal juga tidak pernah bisa dia sembunyikan 100%. Cara Basir yang sekarang memandanginya dari ujung kepala hingga ke ujung kaki mengingatkan Sita pada atasannya itu. Semoga mereka dua orang yang berbeda. Semoga dia salah.
“Tapi masih bisa, kan, Pak?” Pak Basuki mewakilkan Egi bertanya.
“Semoga, ya,” kata Pak Reksha yang kemudian—sesudah dipersilakan—mengekor tuan rumah meninggalkan pekarangan.
Berjalan paling depan, Egi memandu rombongan mengisi ruang tamu. Di sana, mereka berembug. Diskusi yang diselingi sembahyang bersama berikut juga persiapan hal-hal mendasar ruwat itu berlangsung lebih lama dari yang dia suka. Bahkan ketika panggilan sembahyang terakhir untuk malam itu mengudara, Pak Pak Reksha masih saja bersilat lidah menerangkan tetek bengek ritual ruwat yang baginya mustahil terdengar lebih ruwet lagi. Di akhir penuturan, dia gagal membendung gelembung kesal yang jika dia tahan akan meletus bersama sisa kewarasannya.
“Jadi, kita harus tunggu sampai setan-setannya datang, baru… ehm, baru… kita mulai upacaranya?”
Pak Pak Reksha mengangguk.
“Lah tapi, kok, siap-siapnya—”
“Harus kita serang mereka saat mereka lena,” kata Pak Basuki.
“Kalau nggak gitu, nanti percuma,” kata Sita menimpali.
Egi membenahi letak kacamatanya sambil bergantian memandangi ayah dan istrinya. Sejak kapan dua orang itu jadi juru bicara Pak Pak Reksha? Mengalihkan pandangan dari mereka, dia pandangi Basir yang sedari tadi mengamati Sita seakan wanita yang darinya dia belum dikaruniai keturunan itu sedang tak berbusana. Menggelengkan kepalanya, laki-laki yang di sela kesibukannya di sawah dan di kandang mencari tambahan mata pencaharian sebagai ojek daring di kabupaten kecil dengan penghasilan yang sebenarnya mengenaskan itu beranjak dari kursi seraya berkata, “Ya, sudah. Aku tidur dulu. Mumpung ada waktu. Besok masih narik. Nggak apa-apa, kan?”
Pertanyaan itu terutama dia tujukan pada Sita yang sering tidak tahu diri mengajaknya berhubungan badan bahkan saat dia tengah kelelahan. Pernah dia karena terpaksa meladeni hasrat sang akhwat. Hasilnya, dia kesiangan. Padahal, hama wereng sedang gagak-galaknya menguras bulir padi. Jika malam ini skenario serupa itu bisa dia hindari: dia akan berterima kasih karenanya.
“Iya, Bi.” Seulas senyum tipis Sita sunggingkan. Sebagai satu-satunya wanita di rumah, akan kurang elok rasanya kalau dia gagal menunaikan tugasnya memuliakan tamu. Memberi suguhan makanan, minum, dan teman berbincang baginya adalah amanah yang harus ditunaikan hingga paripurna. “Abi istirahat aja dulu.”
Sebelum benar-benar berlalu, Egi kembali bertanya, “Umi mau lanjut jahit lagi habis ini?”
Pupil mata Sita membeliak melebar. Sementara suaminya memilih sampingan ojek, sebagai tambah-tambah uang dapur dia kembali menekuni kegemaran yang dia campakkan saat dia berkuliah di jurusan komunikasi lalu bekerja di kantor agensi periklanan, yaitu: menjahit. Pelanggannya hanya beberapa. Tetangga-tetangga. Namun begitu, dia menikmatinya.
“Ah, iya.” Sita pun ikut bangkit. “Dua hari lagi diambil!”
“Sudah,” kata Pak Basuki saat anak dan menantunya memandangnya seakan meminta kesediannya menemani para tamu sampai nanti ruwat dimulai. Pria lewat setengah abad yang mengaku sudah sembuh berjudi dan bertekad hidup bersih tersebut menyulut rokok kedua puluhnya hari itu lalu berkata, “Serahkan ke Bapakmu. Kalau cuma ngobrol, sampai pagi juga Bapakmu kuat! Hahaha!”
Dan benar saja, Pak Basuki membuktikan omongannya. Lelaki berperawakan rata-rata itu jabani si paranormal yang hanya setahun lebih tua darinya itu membicarakan segala macam hal. Ditemani gelas-gelas kopi dan kepulan asap rokok mereka menjelma teman dekat meski baru pertama berjumpa. Dari obrolan itu dia peroleh informasi mengenai kehidupan Pak Reksha yang penuh lika-liku. Sebelum menjadi tokoh agama lokal sekaligus ahli spiritual pemilik rumah pendopo luas serta beristri tiga yang memberinya sembilan anak, dia hanya seorang gembala. Orang miskin desa. Bukan siapa-siapa.
“Kerja keras itu perlu, Pak Pak Basuki,” kata Pak Pak Reksha. “Tapi bukan segalanya. Harus cerdas juga. Kalau nggak pinter lihat-lihat peluang, ya, paling saya masih angon wedhus dan bebek!”
“Hahahaha, iya. Saya tahu. Tapi, ya, begitulah, Pak. Musuh saya cuma satu: malas!”
“Malas?”
Pak Basuki mengangguk.
“Tapi, sekarang sudah ndak, to? Ada ayam sama telur yang harus Bapak urus, kan?”
“Yah,” kata Pak Basuki sambil sesekali mengusap layar gawainya yang diam-diam dia pakai mencari tambahan dengan bermain slot, “untungnya begitu.”
~bersambung
Cengkerama mereka baru mereda kira-kira mendekati pukul sepuluh malam. Gara-garanya, Basir yang menghabiskan setengah obrolan dalam bisu dan setengahnya lagi dengan duduk-duduk di teras mendadak saja masuk ke ruang tamu dengan mata melotot. Jika bukan karena Pak Reksha yang lekas menanggapi isyarat tersebut, dia yakin dia bisa mati di bawah tatapan itu. Sesuatu memberitahunya untuk waspada. Bukan saja pada bahaya yang mengintai selama ritual nanti namun juga pada … sosk Basir itu sendiri.
Belum sempat Pak Basuki menemukan kejelasan dari remang di tengkuknya, kiso dan keranjang bunga yang tadinya diletakkan di kaki meja tiba-tiba saja disorongkan padanya.
“Bawa ke kamar anak Bapak. Cepat!” perintah Pak Reksha. Arahan itu berkaitan dengan lokasi ritual yang telah disepakati bersama sesudah Basir memeriksa seisi rumah dan menetapkan kamar itu sebagai titik paling kuat guna mementahkan sihir jahat yang mendera. “Bangunkan juga anak Bapak!”
Sigap Pak Basuki berangkat. Dalam perjalanan ke kamar si anak, dia mampir ke kamarnya sendiri yang dibangun belakangan sehingga mengubah interior rumah dan menyempitkan ruang tamu. Di sana Egi masih terlelap.
Sukses membangunkan si anak, dia berderap ke kamar sebelah. Dia dapati Pak Reksha mendahuluinya tiba. Di lantai kamar yang tadinya dikosongkan sudah tergelar sebentang kain merah. Cekatan si orang pintar menata ubo rampe yang dia bawa di dalam tas. Pak Basuki menjumpai setidaknya enam cawan tembaga yang masing-masing diisi kemenyan, sebutir telur, beras merah, beras putih, potongan-potongan tulang yang semoga tulang binatang, dan kerikil.
Lalu, dia melihat tiga cawan tambahan yang masih kosong. Cawan-cawan itu lantas berurutan diisi kelopak-kelopak bunga tujuh rupa, darah segar dari ayam cemani yang baru disembelih, dan… ludah? Meski sudah dijelaskan sebelumnya seperti apa mekanisme ruwat ala Pak Reksha, Pak Basuki masih sangsi pada item yang satu itu.
“Pak? Istri saya mana?” tanya Egi yang entah kapan sudah turut bergabung di kamar. Demi menghindari bau amis darah, dia memilih berdiri dekat-dekat pintu yang terbuka.
Untuk sejenak ketiga pria saling melempar pandangan. Pak Reksha dengan tatapan kesalnya. Pak Basuki dengan tatapan bingungnya. Lalu Egi dengan manik paniknya.
Mengagetkan ketiganya, Basir menerjang ke ruangan dengan Sita dalam gendongan. Perbedaan postur tubuh keduanya menjadikan seakan-akan yang sedang dia bawa adalah bocah belia. Sebelum ada yang bertanya, dia berkata parau, “Dia kejang-kejang tadi. Di bawah meja jahit.”
“Kejang-kejang?” tanya Egi, merangsek ke arah istrinya yang tampak pulas.
“Kesurupan,” kata Pak Pak Reksha. “Sudah kamu sirep?”
Basir mengangguk.
“Tapi ndak yakin aku bakal ampuh sirepnya sampai—”
“Untung tadi dibawa talinya,” kata Pak Reksha yang sejurus kemudian mengeluarkan segulung tali tambang dari tas. “Cepet! Ikat dia!”
“Ikat?” tanya Egi. Siapa yang mau diikat? Ini tidak ada dalam rencana. Yang benar saja!
“Di mana?” tanya Pak Basuki yang lebih tanggap dari anaknya. Rencana bisa berubah. Tidak ada yang tidak wajar di sana.
Tak kalah sigap, Basir serahkan Sita pada Egi yang sekonyong-konyong doyong menggendong istrinya. Sekejap kemudian dia raih tepian ranjang yang dimiringkan menghadap ke tembok. Enggan jadi kecoak gepeng, yang lain pun berhamburan menyingkir. Dalam satu percobaan Basir telah melenyapkan ubo rampe dari pandangan. Membiarkan tangan-tangannya bicara, dia tata kembali kasur dan sprei di atasnya.
Progres buru-buru ini menuai tanya dari Egi dan Pak Basuki yang tadi kewalahan memiringkan itu ranjang. Sementara pertanyaan mereka tersangkut di kerongkongan, Basir berkata pada Pak Reksha, “Masih simetri ini. Bisa, kan?”
Pak Reksha menelan ludah, lalu mengangguk-angguk.
Selanjutnya, tanpa banyak cakap mereka ikat tungkai lengan dan kaki Sita pada keempat sudut ranjang yang kasurnya miring dan seprainya awut-awutan itu. Meski masih dalam baju kurungnya, Sita sendiri tidak tampak lebih rapi dari tempatnya berbaring. Satu betisnya tersingkap. Hijabnya sedikit miring ke kiri.
“Sekarang apa?” tanya Egi yang terjebak antara perasaan terluka, terhina, ngeri, dan murka. Sulit dipercaya. Dia baru saja membantu dua orang asing mengikat istrinya. Terikat seperti itu, Sita tak ubahnya santapan mata. Lihat saja. Dadanya yang membusung. Gundukan di antara kedua pahanya yang tercetak cukup jelas. dia kian menyesali keputusannya.
Seakan menjawab pertanyaan Egi, tiba-tiba langit-langit rumah bergetar. Gemeretak dan gemuruh terdengar membahana. Seolah-olah ada kerbau gila sedang mengamuk di atas sana. Kedap-kedip lampu kamar dibuatnya.
“Ayo!”
Pak Reksha sambar telapak tangan Egi di kiri dan Pak Basuki di kanan. Di seberangnya, Basir melakukan yang serupa. Diawali keduanya, mereka merapalkan mantra yang sudah mereka briefing sebelumnya. Bapak dan anak Pak Basuki-Egi kesulitan di awalnya. Namun, sebentar kemudian mereka bisa mengikuti.
Kian nyaring gangguan dari atap, kian lantang mereka meneriakkan mantra. Sampai kemudian, mata Sita membeliak terbuka. Mengikuti mata, mulutnya pun menganga. Tidak ada yang keluar dari sana kecuali asap hitam yang bergerak ganjil seakan dia bukan gas melainkan satu koloni ngengat sebesar biji-biji mentimun yang seratus persen sedang marah besar. Asap itu berputar-putar hingga pada satu kesempatan dia buat keempat pria dewasa yang berdiri mengerumuni ranjang terpental ke empat arah mata angin.
Egi hilang kesadaran saat itu juga. Ketika dia kembali membuka mata, dia telah kembali di ranjang ayahnya. Apa yang terjadi?
“Istrimu,” kata Pak Basuki yang Egi temukan duduk di tepi ranjang, memunggunginya, “baik-baik saja. Demit di tubuhnya sudah dibuang. Rumah juga sudah aman.”
Merasakan ayahnya melupakan bagian terpenting dari potongan informasi yang dia sampaikan namun terlalu lemah untuk melompat bangkit, Egi bertanya, “Tapi?”
“Dia perlu ruwatan khusus.”
“Berapa lama… aku pingsan?”
“Sarjo dan Basir minta kita percaya ke mereka.”
“Bull.. shit. Bantu aku bangun, Pak.”
Alih-alih meraih lengan anaknya, Pak Basuki justru turun dari ranjang. Tanpa menatap mata Egi, dia berkata dengan suara pecah, “Maafkan Bapak, Nak.”
“Pak, bantu—”
Punggung Pak Basuki melengkung ke depan lalu menggigil.
“Ini semua salah Bapak. Kamu bisa mati tadi! Kalau dulu Bapak nggak biarkan Ibukmu pergi. Kalau aku kejar dia… akan beda jadinya. Kamu nggak akan suka mbolos. Kamu nggak akan kuliah seni. Kamu akan jadi orang betulan. Orang kaya. Terpandang. Ini salahku. Aku merasa aku bisa besarin kamu. Aku buta. Aku ….”
~bersambung
Sementara Pak Basuki melanjutkan ratapannya yang mengaduk perasaan Egi dengan sedemikian rupa hingga dia memilih kembali memejamkan mata sembari berharap kegelapan menelan kesadaran dan pusingnya, di kamar sebelah, Pak Reksha dan Basir tengah sibuk ‘mengobati’ Sita yang perlahan-lahan siuman sebagai dirinya sendiri berkat usapan-usapan pada paha dan buah dadanya. Di bawah deraan rangsangan, dia mendesah pelan.
“Hmpph….”
Sita lalu membuka matanya.
“Eh, sudah bangun, Cah Ayu?”
“Ini … di mana?”
Pertanyaan Sita keluar dalam bisikan. Kepalanya serasa diisi kapas. Sendi-sendi tulangnya berkarat. Napasnya berat dan cepat. Dan yang paling parahnya, kulitnya seakan terbakar. Ada yang sedang menggerayangi daerah-daerah sensitifnya.
Sita fokuskan pandangannya, dan… astaga! Pak Reksha?! Basir?! Sedang apa mereka?
“Pak Reksha! Tangan saya kenap—“
“Jangan takut,” ujar Pak Reksha yang duduk di depan selakangan Sita. Rok panjang wanita berjilbab itu dia tanggalkan segera sesudah tali yang mengikat sepasang kaki jenjangnya dia buka. Gamis biru yang membungkus mereka disibakkan bagi semua mata. Sedikit demi sedikit keduanya dia jamah. Dia belai. Dia rangsang. Dia jauhkan. Dia renggangkan. Pelan, jemari-jemari sosis Pak Reksha menjelajah kian dalam. Kian ke atas. Kian mengarah ke segitiga paling berharga si akhwat.
Mendapati bingung mengotori paras keibuan Sita, Pak Reksha berkata, “Mbak Sita sedang kita ruwat. Setan-setan yang masuk ke rumah ini, masuknya lewat Mbak Sita. Nah, setannya sudah kita usir. Tapi, biar ndak kejadian lagi, ini Mbak harus kita buat puas.”
Puas?
Pertanyaan itu menggantung di benak Sita sementara satu per satu kancing bagian gamisnya dibuka oleh jemari-jemari kasar nan perkasa kepunyaan Basir. Berbeda dari si bos yang telaten, raksasa itu seperti sedang tak ada waktu. Deru napasnya menggebu. Ototnya kaku. Matanya membara beku. Kesabarannya habis begitu dia sentuh halus permukaan fabric BH tipe soft-cup ukuran 3D yang Sita kenakan.
Menyeringai, Basir renggut BH itu putus dalam satu sentakan.
Sita pun memekik kaget. Dada membusungnya kian cembung. Sekejap kemudian, sepasang gunung kembarnya jadi santapan mata para pria. Bulat dan sama besarnya. Putingnya yang cokelat gelap tampak kontras dengan kulitnya yang mulus kuning langsat. Meski sudah mau kepala tiga, payudara Sita masih sekencang seperti saat dia masih gadis. Wajar. Dia belum pernah melahirkan. Belum ada anak yang harus dia susui. Selain oleh dirinya sendiri, buah dadanya hanya pernah disentuh Egi.
“Wah, wah, wah. Apik banget susumu, Mbak,” kata Pak Reksha mengomentari buah dada Sita yang secara alami memang tampak pejal, kenyal, dan mengkal.
Memerah muka Sita mendengarnya. Lancang sekali Pak Reksha ini. Padahal baru melihat sekali. Sita jadi kepikiran Egi. Yang jarang memuji. Yang agaknya harus kursus menyenangkan istri. Biar kalau bersebadan maunya nggak gelap-gelapan.
Plak!
Basir tampar payudara Sita yang kiri.
Plak!
Basir tampar juga yang kanan.
Selagi si akhwat mengaduh kesakitan, Basir caplok mereka bergantian. Dia sedot-sedot mereka. Dia gigit-gigiti. Jemarinya tak mau ketinggalan. Dia peras mereka kesetanan.
“Abi!” Air mata Sita berhamburan dari pelupuk mata. Sebagai seorang istri yang setia, dia merasa telah gagal menjalankan tugasnya. Sebab, meski terkesan masih menolak, diam-diam akhwat itu menikmatinya juga. “Enggggmphh…. Hmmpphhh…. Aaabiii….”
“Ck,ck,ck. Jangan berisik, Mbak. Mbak mau setan-setannya balik ke sini?” kata Pak Reksha yang sudah sukses mengangkangkan paha Sita degan mendesakkan perutnya sedekat mungkin dengan vagina si akhwat dan hanya menyisakan sedikit ruang bagi jemarinya beroperasi. Pertama-tama, dia raba gundukan serupa kue itu dari luar celana dalam berenda. Setiap jengkalnya dia beri perlakuan sama. Dia ingin menepati janjinya. Akan dia pastikan malam ini dia bawa bidadari itu pulang ke surga. Ke nirwana.
“Abi!” teriak Sita, berharap tiba-tiba Egi akan muncul lalu menyelamatkannya. “Tolong Umi! Huhuhuhu…… Aaaabiii….”
Mungkin terusik erangan bercampur tangisan Sita, Basir berhenti menyusu. Memajukan badannya, dia posisiskan wajahnya di depan hidung bangir korbannya. Selagi yang bersangkutan tercekat ketakutan, dia lumat bibir yang setengah terbuka. Dia surukkan lidahnya ke rongga mulut Sita. Dia cari-cari lidah Sita. Helai-helai rambut gondrongnya yang berjatuhan meski sudah diikat kini mengubur Sita. Sembari memagut ganas lawan mainnya, dia lanjutkan tugasnya menggarap dada, ketiak, pundak, serta leher Sita. Hijab lebar hitam Sita gagal membendung serangannya. Fakta bahwa kedua tangan Sita masih terpancang ke ranjang memberinya leluasa.
“Harap maklum, Mbak,” kata Pak Reksha. Lelaki tambun itu punya jemari kini sedang menyelinap merabai pusaka belah tengah yang dari bentuknya memang diciptakan untuk dijamah. Halus rambut-rambut kemaluan yang dicukur rapi sedikit membuatnya geli. Sensasi itu dia balas dengan memainkan belahan bibir memek yang becek.
Menilai Sita sudah semakin terbakar birahi, Pak Reksha tak tahan untuk terus membohongi. Ya. Tidak ada ceritanya Sita membutuhkan ruwat. Ubo rampe sesajen sudah Basir bereskan dari kolong ranjang. Dia dan asistennya bisa saja pulang sekarang. Tapi, bukan begitu mereka terbiasa bekerja. Keduanya tidak akan pergi sebelum memetik upah utama mereka.
Berkatalah orang pandai itu kemudian, “Dari kemarin, dia nanya-nanya soal Mbak terus. Kapan? Kapan? Yah, namanya anak muda. Kalau sudah mau, harus ada yang diajak diadu. Lumrah. Seumuran dia saya juga sama. Maunya yang baru. Yang baru. Bosen pakai yang lama. Padahal ada tiga yang siap pakai kapan saja, lho. Tapi, ya, begitu. Sudah berumur istri-istri saya itu. Yang paling muda saja sudah mau empat puluh. Huh. Ah. Ketemu juga itil Mbak. Hehehe. Saya geser, ya, Mbak, cawetnya? Mau lihat.”
Bukannya Sita enggan menjawab. Bukan juga dia tidak ingin menendang gigi tonggos si babi durjana. Dia hanya sedang kewalahan. Baru kali ini dia diserang dari dua arah. Dia marah. Pada bedebah-bedebah yang sedang menggarapnya. Pada Egi yang entah sembunyi di mana. Pada dirinya sendiri yang … diam-diam menerima perlakuan mereka. Sentuhan-sentuhan mereka terasa istimewa.
Sejak remaja, Sita sudah penasaran dengan seks. Dengan hubungan badan. Beberapa kali dia tonton adegan film dewasa. Dia ingat detil-detilnya. Menit demi menitnya. Pada saat yang sama, Sita sadar dia hanya boleh mempraktekannya dengan pasangan halalnya.
Sebagai cacatan, Egi bukan pacar pertamanya. Dia pernah dipacari empat mahasiswa sekaligus waktu masih di kampus. Tidak satu pun dari keempatnya dia beri izin menyentuh selain tangannya. Itupun dia sambil membatin. Memohon ampun atas dosa-dosanya. Prinsip Sita membawanya kemudian pada kajian-kajian yang di sana dia bertemu Egi. Pada laki-laki itu juga dia akhirnya serahkan mahkota perawannya.
Prinsip yang sama sekarang mustahil dia jaga. Raksasa yang sedang mencumbunya terlalu buas. Terlalu ganas. Beringas. Dia pernah bertukar ludah dengan Egi, tentu saja. Sayangnya, permainan Egi seperti bocah bau kencur. Baru kali ini dia rasakan relung-relung sukmanya dijelajahi. Dijajaki. Digagahi.
Belum lagi, di bawah sana, Pak Reksha sedang memilin-milin serta menarik-narik kelentitnya. Seperti sedang disetrum rasanya. Sakit, tapi enak juga.
Lawan! Lawan! Batinnya menjerit.
Apa daya. Dia hanya wanita bertinggi 165 dan berbobot 62 yang jarang dijamah suaminya. Benaknya dihajar habis-habisan. Kiri-kanan. Atas-bawah. Kalah sudah, dia kalah.
Menyerah.
Crat…. cratt….. crattt!
“Waaah!” seru Pak Reksha. Sedikit pun tak tampak dia mencemaskan potensi kegiatannya dicampuri pengganggu. Pintu sudah dia tutup rapat. Kepala Egi tadi terbentur cukup keras. Tanpa perlu dia ‘obati’ juga pria berkacamata itu sudah menyerahkan istrinya. Nasib sedang memihaknya. Sejauh ini masih sesuai rencana. Semburan ejakulasi Sita yang bercampur sedikit pesing kencing sama sekali tak menyurutkannya. Yang ada, dia justru kian bahagia. Tanpa rasa jijik dia jilat jemarinya yang basah dan sedikit licin sekaligus lengket. Aroma tubuh Sita yang sedang aktif-aktifnya membuat birahinya berpesta. Ya, pesta. Malam ini dia akan berpesta. Akan dia taklukkan kuda betina barunya. Akan dia tambahkan Sita ke koleksinya.
“Enak, Mbak, ngecrotnya?” tanya Pak Reksha sambil beradu tatap dengan Sita selama beberapa detik lamanya. Dengan pantat masih di tempat semula, laki-laki itu telanjangi bagian atas tubuhnya. Baju basah itu dia onggokan saja di kaki ranjang yang meretih lirih di bawah beban tiga orang di atasnya. Terpampanglah kemudian perut gentongnya. Rambut-rambut di dada yang mengarah turun ke perutnya dia pamerkan belaka.
Selesai setengah menelanjangi diri, dia lalu beringsut ke samping. Dia naikkan satu paha Sita ke pundak. Lantas, dia turunkan kepalanya hingga berhadap-hadapan dia dengan gerbang surga. Jika diminta menilai dari casingnya, dia akan beri tempik itu skor 8/10. Nilai itu akan tetapi, bukanlah segalanya. Ada wangi yang khas dari sana. Bukan wangi tempik wanita desa biasa. Bahkan rongganya pun berbeda. Dugaanya, hal ini disebabkan Sita dulunya orang kota yang melek kebersihan. Melek kesehatan. Ditambah, dia taat beragama. Garansi terjaga.
Ck, ck, ck.
Pak Reksha julurkan lidahnya dia. Saat ujung indera perasa itu berjumpa lipatan daging memek Sita, dia tahu sebentar lagi dia akan bisa menunggangi si akhwat. Namun, dia tidak mau buru-buru. Bukan hanya dia sedang ingin memberi Basir, anak haramnya, sedikit lebih lama menikmati porsinya; lelaki itu juga ingin Sita mendapatkan pengalaman paling mengesankan dalam hidupnya. Dari konsultasi Egi dan istrinya dulu, dia sudah tahu. Membebaskan pasangan itu dari guna-guna mereka yang tidak suka pada keduanya baru setengah jalan merampungkan masalah. Egi bukan jodoh yang tepat bagi Sita. Sita berhak mendapatkan yang lebih.
Dan dari siapa Sita akan mendapatkannya kalau bukan darinya?
Saat dirasa sudah cukup dia melumat tempik Sita, Pak Reksha tegakkan tubuhnya. Dia lalu perintahkan Basir agar memberi si akhwat kesempatan menyambung nyawa. Tidak lucu kalau pembinalan yang sedang berlangsung gagal karena objeknya tewas duluan.
Sementara Basir menyingkir, Pak Reksha dekati kepala Sita. Ke telinganya, dia lalu berbisik. Bisikan itu membuat Sita membuka mata. Lalu menggelengkan kepala.
“Nggak, Pak. Nggak. Udah…. Jangan. S-saya… “
“Apa?” tanya Pak Reksha sambil membenahi kerudung Sita.
“Saya istri orang, Pak. Ini… ini dosa. Zina!”
“Lah? Memang. Tapi Mbak suka, kan?’
Sita menggeleng.
“Lha, yang tadi? Ngecrot juga lho Mbak Sitanya. Hehehe.”
Selagi pentilnya disentil-sentil si tua bangka, Sita katupkan mulutnya. Dia gigiti bibirnya. Yang tadi itu… apa? Belum pernah dia merasakannya. Dia pernah menonton bokep yang di sana si akhwat terkencing-kencing seperti anjing pesing. Apa dia juga baru mengalaminya?
“Saya tahu, kok, Mbak, rahasianya Mbak.”
Sita melirik sayu pada lelaki di sampingnya.
“Mbak tidak pernah dipuaskan suami, Mbak.”
“Tahu… dari mana?”
Pak Reksha terkekeh singkat.
“Kelihatan, Mbak.”
“T-tapi, kan, saya nggak pamer-pamer aurat.” Sita mendelik pada Pak Reksha dan Basir—yang tengah membenahi kuncir rambutnya. “Saya wanita baik-baik, ya!”
“Mbak memang ndak pamer tetek sama memek Mbak ke orang. Mbak pamernya lain. Mbak pamer kalau Mbak ini berbeda. Kalau Mbak ini… solihah. Yang sayangnya, pas pamer Mbak juga bertanya-tanya. Apa, iya, semua istri dibuat kecewa suaminya? Atau, jangan-jangan Mbak satu-satunya? Nggak enak, lho, Mbak. Udah kesepian. Penasaran lagi.”
Kata-kata Pak Reksha meninggalkan Sita dengan pikirannya sendiri. Laki-laki berparas amit-amit itu bak cermin ajaib yang membeberkan sisi tergelap dirinya. Sisi paling privatnya. Sisi yang tidak bisa dikunjungi hanya dengan usapan dan sentuhan fisik semata.
“Tapi tenang, Mbak. Mbak Sita sekarang punya kita. Punya saya. Mbak ndak akan lagi penasaran. Mbak akan saya puaskan.”
Sita menelan ludah yang terasa sangat aneh bila dibanding biasanya.
“Nggak, Pak. Udah. Yang tadi itu… cukup. Saya udah puas.”
Pengakuan Sita mengundang gelak Pak Reksha. Terguncang-guncang perut pria itu dibuatnya. Tiba di penghujung tawa, dia sempatkan berkata, “Yang tadi itu baru menu pembuka, Mbak. Pemanasan. Belum juga masuk ronde pertama.”
“Ronde… pertama?”
Sejauh yang Sita dapati dari Egi, tidak ada yang namanya ronde pertama. Mereka bermain sekali dan… sudah. Selesai. Kalau ada yang pertama, berarti akan ada yang kedua. Yang ketiga ….
“Malam masih panjang, sayang,” ucap Pak Reksha. Dia kecup dahi Sita. Turun dia dari ranjang. Dia tanggalkan kemudian celana beserta sisanya. Telanjang bulat dia lalu kembali hampiri betinanya. “Pernah nyepong belum? Belum, ya?”
Sita bungkam.
“Mau coba?”
Cepat Sita menggeleng saat penis melengkung Pak Reksha mendekat. Jelas benda itu lebih besar dari punya Egi. Lebih panjang. Lebih gagah juga. Kepala jamurnya gelap, mengkilap.
“Oh?” Pak Reksha menepuk-nepuk pipi Sita dengan kontolnya. Tak berhenti di sana, dia gesek-gesekkan juga batangnya ke jilbab si akhwat. Dari atas, dia lalu bergerak ke bawah, ke gunung kembar yang menggoda. Dia akhiri petualangan kecilnya dengan mengusapkan kepala kontolnya ke ketiak Sita yang minta bersih tanpa noda. “Yakin?”
“Pak…. hmmmssshhh… tolong lepasin saya,” kata Sita memalingkan muka. Bau kemaluan Pak Reksha membuatnya mual. Belum pernah dia cium aroma sekuat itu. “Plis, Paaakkk. Saya mohonn….”
“Nanti, ya?” kata Pak Reksha sambil mengocok sendiri kemaluannya yang belum sepenuhnya bangun. Yang masih bisa lebih tegak lagi berdiri. Sembari naik ke ranjang lalu bersiap di antara kedua kaki Sita, dia berkata, “Sekarang, Mbak icipi dulu kontol saya.”
Sita sudah berontak saat kakinya kembali disentuh. Dia semakin kuat menendang-nendang udara coba menggulingkan si celengan babi bernyawa. Nahas, dia melawan seorang pro. Masing-masing pahanya dijepit di ketiak manusia jahanam yang sempat dia kira ahli agama penolong sesama. Lenga-lengan yang melingkari mereka lalu turun ke pantatnya. Mencengkeram bokongnya. Salah satu dari keduanya kemudian bergerak ke tengah.
Ke tengah.
Masih ke tengah.
Sita sadar apa yang akan menimpanya. Dia tahu apa yang akan terjadi jika sampai kepala jamur itu memasukinya. Tubuhnya akan menyatu dengan tubuh laki-laki yang jauh lebih tua darinya. Yang lebih pantas menjadi ayahnya. Yang tidak punya hak menjamahnya. Yang akan membuatnya mengkhianati perkawinannya.
Sebelum terlambat, Sita harus—
“Paaak…. Ingat, Pak!”
Ujung kemaluan Pak Reksha mulai menyibak lipatan vaginanya.
“Bapak itu ustaaa—”
Suara Sita putus di tengah jalan. Dalam satu dobrakan kasar Pak Reksha menghunjamkan kontolnya menembus pertahanan Sita. Besarnya rudal itu melebihi perkiraanya. Keras dan kokohnya merobek memeknya.
“Lho? Kok?” Bergantian Pak Reksha memandangi kontol yang baru sepertiga mendekam dalam hangat tempik Sita yang menggembung. Ada darah di sana. “Mbak masih perawan?”
Sita jawab Pak Reksha dengan rintihan.
“Walah. Rejeki nomplok ini namanya.”
Kepada Basir yang juga ikut sudah telanjang dan menunggu aba-aba, dia berkata, “Ini, lho, lihat. Merah. Ck, ck, ck, ck. Sekecil apa titit suaminya, ya?”
“Aku boleh coba?” tanya Basir, ujug-ujug mendekat.
Dengan sapuan satu lengan Pak Reksha usir anak haramnya.
“Sana. Kamu jebol dulu mulutnya. Bapak mau jebol memeknya.”
Menahan deraan perih yang menumpulkan akal, Sita bergumam, “Ampun…. Udah…. Jangan…. Udah…. Ud—Aaaah!”
Tanpa ampun Pak Reksha mengabaikan permintaan Sita. Dalam satu hentakan dia amblaskan kontolnya.
“Aarghh. Hangatnya….”
Jembut keriting beruban Pak Reksha berkelindan dengan jembut halus Sita. Dia biarkan otot-otot vagina akhwat itu beradaptasi dengan lingkar kontolnya. Sejak meminang istri ketiganya, Pak Reksha sudah katakan pada diri sendiri untuk hanya memangsa mereka yang sudah bersuami. Dia bangga atas kendali diri tersebut. Namun, pada kesempatan kali ini… dia tak hendak menolak!
Kapan lagi dapet obat awet muda, kan, ya?
“Suaminya Mbak pasti kecil, ya, kontolnya?” tanya Pak Reksha sambil mengelus bagian belakang paha Sita. Berhati-hati agar wanita berjilbab itu tidak pingsan, dia mundurkan pantatnya. “Aduh… kok, masih gigit banget ini, Mbak? Ada pelumasnya padahal, lho.”
Lain dengan si-guru-agama-abalabal-begundal-anak-sundal yang sedang tersenyum lebar, Sita yang tengah mengalami lagi malam pertama berharap semuanya hanya mimipi belaka. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dosa apa yang dia perbuat sampai-sampai dipaksa melayani lelaki yang bukan suami? Tuhan, maafkan hamba. Ampuni hamba. Sembari hatinya berdoa, Sita menggeliat-geliat macam ulat kena sengat. Belum terima dia akan kenyataan bahwa dia kini PENUH noda. Selamanya, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya.
“Jangan dilawan, Mbak,” kata Pak Reksha, mata lurus membius Sita. Tangan-tangan laki-laki itu kini memegangi pinggang ramping Sita agar tidak ke mana-mana. Agar otot-otot memek Sita lebih rileks. Lebih terbiasa dengan kontol yang sedang mengganjalnya. Rapatnya bibir si akhwat memberitahunya bahwa dia belum seluruhnya diterima. Masih ada penolakan di sana. Dia yakin tak untuk waktu yang lama.
Namun begitu, akan lebih sempurna jika penundaan yang tidak perlu ini dibuang saja. Sembari menghela dan menghunus dia punya pusaka, Pak Reksha bujuk mainan barunya, “Ayo, Mbak. Jangan malu-malu. Kalau mau mnedesah, desah saja.”
Pelan tapi pasti, Pak Reksha rontokkan benteng bata per bata tembok pertahanan Sita. Pada akhirnya, menyerah juga dia. Berjuta sensasi memabukkan yang menyertai pompaan penis laki-laki itu melemahkan imannya. Rasanya terlalu enak. Terlalu nikmat. Bibirnya pun akhirnya saling menjauh. Desis tipis lolos dari sana. Lalu, di luar kuasanya, dia mulai mendesah.
“Hmmmphhh… Enghhhhh…. Ssshhhh….. Aaaahhhkk….”
“Yaaa, gitu, Mbak! Jangan malu-malu. Hahhahaaahaa.”
“Aaaahhh…. Paakkk… hmmmpphhh…… Pelan-pelan…”
“Ini juga pelan, kok, hehehehe,” kata Pak Reksha yang detik demi detik menaikkan tempo genjotannya.
Iri dengan keduanya yang asik kawin tanpa keterlibatan dirinya, Basir pun mendekat. Kontol hitam legam sepanjang 20 centinya dia acungkan ke muka si akhwat untk diisap. Entah karena keenakan digenjot ayahnya, atau karena terpesona urat-urat yang menonjol pada penis tak bersunatnya; mata Sita melotot seperti mau meloncat dari kepalanya. Enggan memusingkan, Basir lesakkan benda itu ke celah bibir Sita.
Saat hanya seperlima saja yang masuk, Basir jambak jilbab Sita. Dia miringkan wajahnya. Ukuran kontol yang melebihi rata-rata orang kita seketika menggembungkan pipi Sita. Dalam satu paduan irama, dia setubuhi mulut yang biasa terjaga. Yang rutin dipakai mengaji. Mengucapkan hanya yang baik-baik saja.
Sementara, di bawah sana, Pak Reksha lanjut menggempur memek Sita. Lendir kemaluan keduanya menciptakan bunyi berkecipak saat sepasang kelamin itu bertemu. Beradu.
“Aaaaah… aaah… aaah… Lonteeeee…… Aku keluaaar!” raung Pak Reksha yang hanya bertahan kurang dari lima menit menyetubuhi memek Sita. Dia cabut kontolnya sebelum dia semburkan sperma putih kekuningan yang kental dan panas ke sekujur badan Sita. Kuatnya semburan itu bahkan mencapai leher Sita yang Basir gerakkan maju mundur mengoral penis yang bagi Sita lebih mirip kontol kuda daripada kemaluan manusia.
Di waktu yang berbeda, Pak Reksha akan malu dengan performa busuknya. Biasanya, dia mampu bertahan lebih lama. Sepuluh menit sekurang-kurangnya. Akan tetapi, kali ini dia coba memaklumi. Pasalnya, tidak pernah terbayang dia akan mencicipi tempik perawan lagi. Jadi, tidak apa-apa. Kali ini dia keluar cepat. Toh, malam masing panjang. Batangnya masih keras. Dia tidak butuh obat kuat untuk tetap tegak.
Tidak, saat di hadapannya tergolek pasrah badan seksi seorang akhwat yang terawat.
Tidak, saat lobang surgawi Sita masih berkedut mengundangnya.
Dia akan tancap gas lagi nanti sesudah debar jantungnya berhenti coba membunuhnya. Untuk sekarang, dia cukup mengusap-usapkan kepala kontolnya ke itil wanita itu; memberitahunya bahwa dia akan dimasuki lagi.
Ah, indahnya, batin Pak Reksha sambil melihat lelehan pejuh di payudara mengkal Sita yang sekarang dari tepian bibir akhwat itu juga meleleh liur akibat dipaksa terus menyepong Basir.
Belum selesai Pak Reksha mengulur rehatnya, tiba-tiba saja dia dengar suara selain geraman Basir dan “glok… glooohk… ohhhk… aoohkkk….” Sita. Asalnya dari luar kamar. Pak Prasojo arahkan mata ke jendela ganda kamar yang ditutup tirai.
Tadi itu apa?
Kucing?
~bersambung
Dugaan Pak Reksha hanya setengahnya meleset. Sebab, sumber suara barusan adalah Pak Basuki yang menyenggol pot bunga di bawah jendela. Saat tatapan si dukun mengarah padanya, buru-buru dia meringkuk, berharap dia bisa menjelma kucing atau binatang sejenisnya. Harapan ini tidak datang tiba-tiba.
Dari celah antara tirai dan kaca jendela, Pak Basuki sempat mengintip ke dalam kamar. Letak jendela bersebelahan dengan kepala ranjang mencegahnya melihat apa-apa saja yang Pak Reksha dan Basir tengah lakukan. Tapi, dia berhasil menangkap lebih banyak dari yang dia peroleh sewaktu tadi mengintip dari lobang kunci pintu kamar. Dia tinggalkan Egi saat tangisannya ternyata malah menina bobokkan anaknya. Dia lalu mendengar teriakan wanita. Curiga, dia sambangi kamar sebelah. Tidak salah lagi. Sesuatu sedang terjadi pada Sita. Setibanya dia di depan kamar, bukannya membuka pintu, dia justru berlutut dan mengintip. Bahkan saat itu pun, dia cukup yakin menantunya sedang dilecehkan oleh Pak Reksha dan Basir.
Gila.
Biadab.
Pembaca yang sangean perlu ketahui, Pak Basuki kita ini setelah ditinggal sang istri jadi kerap berkunjung ke lokalisasi. Jadi, selain berjudi, dia buang-buang juga duit kerja serabutannya untuk jajan sana-sini. Yang anehnya, meski punya tempat membuang pejuh, dia masih saja menyimpan konak terhadap Sita. Padahal, menantunya itu wanita yang taat beragama. Selalu berpakaian tertutup. Bahkan saat di dalam rumah yang mereka tinggali bersama di ibukota. Habis mandi pun Pak Basuki belum pernah mendapati Sita tanpa jilbabnya.
Apa justru dari sana ketertarikan Pak Basuki berasal? Dari penasaran akan apa yang tersembunyi di baliknya? Ah, tapi muslimah berhijab di ibukota bukan hanya Sita saja! Eh, tapi mereka bukan Sita. Egi pastinya punya pertimbangan tersendiri memilih Sita. Hmm, apa ada kualitas dalam diri Sita yang mengingatkan Egi pada ibunya? Pada mantan istri Pak Basuki?
Pak Basuki sendiri mengakui, susah menahan godaan untuk tidak menjamah Sita. Harus dia pendam hasratnya. Demi anaknya. Paling-paling, saat sudah tidak tahan, Pak Basuki akan mengocok sendiri kontolnya sambil membayangkan dia mengentot Sita di belakang Egi. Pikiran nakal ini makin menjadi setelah mereka pindah ke desa. Di kabupaten yang dia tinggali sekarang memang ada juga lokalisasi. Tapi tidak banyak. Itu pun yang ada barang-barangnya jelek-jelek. Jadilah nafsunya pada Sita dia pelihara. Tadi saat membantu mengikat Sita, diam-diam dia ngiler juga.
Ah!
Dan sekarang, malah Pak Reksha dan Basir dulu yang menikmati si akhwat!
Monolog Pak Reksha yang dia curi dengar dari balik pintu mendidihkan darahnya. Membuatnya otaknya pindah ke selakangan. Buru-buru dia pun menghambur ke kamarnya sendiri. Tanpa membangunkan Egi, dia buka jendela kamar lalu melompat ke luar. Menyusuri tembok rumah, dia tiba di jendela kamar Sita dalam dua langkah.
Saat mengintip, yang terlintas dalam kepalanya adalah dia ingin menyaksikan semuanya. Tentu saja, Pak Reksha dan Basir tidak akan membiarkannya. Dia tidak diajak. Yang tidak akan jadi soal kalau dia adalah kecoak atau semut atau nyamuk atau cicak yang bisa ikut menyimak tanpa ada yang peduli.
Oh, andai saja.
Dalam keadaan menyedihkan itu—merangkak di dekat pot bunga—dan larut dalam pikirannya sendiri, Pak Basuki terlambat menyadari. Jendela kamar Sita tahu-tahu dibuka dari dalam. Sebuah lengan tiba-tiba menyambar kerah bajunya. Seperti gombal amoh dia dipungut ke udara.
Yang Pak Basuki tahu selanjutnya, dia sudah ada di dalam kamar. Badannya dihempaskan ke meja rias. Dari sana, dia bisa memandang ke seberang ruangan. Ke arah ranjang yang di atasnya tergolek tubuh Sita; tangan terikat, gamis tersingkap, paha mengangkang, dada telanjang belepotan sperma. Jejak-jejak air mata menganak sungai pada pipi yang merona. Bibir ranumnya terbuka. Ludah meleleh dari tepinya.
Hijab yang masih membungkus kepalanya entah mengapa membuat penis Pak Basuki lebih keras dari yang sebelumnya.
Sayang, Pak Basuki tidak bisa lama-lama menikmati pemandangan itu. Usai menutup kembali jendela, Basir berdiri menjulang di depannya. Raksasa itu telanjang. Kemaluannya tegak menantang. Pundak-pundak lebarnya mengubur wajah Pak Basuki dalam bayang-bayang.
Dilumpuhkan kejut dan takut, Pak Basuki gagal menghalau Basir yang tiba-tiba mencekik lehernya.
“Pak Basuki!” sapa Pak Reksha yang belum bergerak dari selakangan Sita. “Saya kira siapa.”
Mendengar nama mertuanya, Sita mengerjapkan mata. Lidah, gusi, bibir, dan rahangnya kelu luar biasa. Basir menyetubuhi mulutnya dengan semena-mena. Jika bukan karena kehabisan oksigen, dia yakin dia akan mati tersedak ludahnya sendiri.
Bagaimana tidak, batang kejantanan Basir disodokkan dalam-dalam hingga mentok ke kerongkongan Sita. Pengalaman pertamanya terlibat seks oral itu terasa akan berlangsung selamanya. Sampai kemudian, tiba-tiba Basir menjeda deritanya. Selama sesaat, sutas liur bercampur lendir kental menghubungkan keduanya.
Berhenti terbatuk-batuk, Sita coba melihat ke bawah. Ke arah vaginanya yang baru diobok-obok Pak Reksha. Ngilu mengiringi setiap denyutnya. Pak Reksha sendiri sedang tampak berbisik-bisik ke telinga Basir. Sejurus kemudian, pria gondrong itu berderap ke jendela.
Enggan bersitatap dengan pemerkosanya, Sita pejamkan matanya sembari mengatur napasnya. Kesemutan menjalari tangannya. Bahkan hanya untuk menggerakkan jemarinya, dia tak bisa.
Dalam keadaan itu, Sita luput menyadari kehadiran Pak Basuki. Kalau bukan karena namanya disebut Pak Reksha, dia tidak akan tahu. Didorong penasaran, dia ikuti ke mana pemerkosanya memandang. Di antara lengan-lengan kekar Basir, Sita mengenali kepala botak sang mertua.
Entah dengan kekuatan dari mana, Sita berhasil menemukan kembali suaranya. Serak dia berteriak, “Paaak! Tolong saya!”
Pak Basuki melotot ngeri. Terdengar gumaman tak jelas dari celah bibirnya. Mungkin sedang mencoba memberitahu bahwa Sita salah orang.
Menolongnya?
Dia saja tidak bisa menolong dirinya sendiri. Daripada Egi, dia lebih terbiasa bekerja kasar; itu benar. Tapi jika dibandingkan dengan Basir; dia simply tidak punya massa otot yang diperlukan untuk sekadar mengimbangi. Tangan-tangannya yang bergerak-gerak mencakar-cakar lengan kanan si raksasa hampir-hampir tak berdampak apa-apa. Jemari besi yang mengunci lehernya menolak merongga.
Kenyataan ini mungkin lolos dari Sita yang lanjut merajuk minta ditolong; tapi tidak dengan Pak Reksha. Tidak juga dengan Basir. Sementara si dukun terpingkal-pingkal, Basir terkikik geli.
“Ahhahaha, hahhaaaa….”
“Eehehehehe.”
“Aduh, aduh…. Pak Basuki! Bapak dengar? Menantu Bapak minta ditolong ini, lho.”
Merasa lebih terhina dari sebelumnya, Sita berhenti merengek. Dalam diam, dia biarkan air matanya tumpah lagi.
“Ayo, Pak. Tolong dia. Hahaahhahaha. Ayooo…..”
“Kalian tidak akan lolos,” gumam Sita, pegal dan ingin binasa.
Tawa Pak Reksha memelan, lalu lenyap. Sambil memainkan itil Sita dengan gesekan kontolnya, dia bertanya, “Mbak bilang apa tadi?”
Gigi bergemeletuk, Sita menyalak, “Ssshhhh… khaaalian kira kalian nggak ahhhkan dapat ganjarannya? Hmmmphh?!”
“Gan… jaran?” Pak Reksha membeo seraya mulai memaju mundurkan pinggulnya tanpa bermaksud menggenjot lagi lobang Sita.
“Asshhhh…. ahhhkan akuhh… laporkan khhalian…!”
“Ke siapa?”
“Polisihhh!” Suara Sita pecah dan terdengar lemah. “Warga! Siapah aja!”
“Oh?” Pak Reksha menikmati mili demi mili pergesekan alat kelaminnya dengan alat kelamin Sita. “Dan mau bilang apa Mbak ke mereka?”
“S-saya diperkosa!” Sita buru-buru menggigit bibirnya. Susah sekali ternyata bicara sambil digoda. Perlu beberapa detik sebelum dia kembali buka suara. “Ada saksinya!”
“Ahhhh! Gitu….”
Menoleh Pak Reksha pada Basir. Membaca isyarat mata ayahnya, Basir mendekat. Dia seret Pak Basuki bersamanya.
Luapan kemarahan Sita berganti ngeri saat Pak Basuki dibawa ke ranjang. Dia memekik kaget saat wajah mertuanya disurukkan ke payudaranya yang terbuka. Ujung-ujung kaku kumis kasar laki-laki itu membuatnya menggelinjang.
“Bagaimana,” kata Pak Reksha yang berhenti memaju-mundurkan kontolnya demi memegangi pergelangan kaki Sita yang dia bentangkan lurus ke samping sehingga semakin terkuak lobang kemaluannya, “kalau saksinya disogok dulu, Mbak Sita? Apa Mbak yakin dia masih akan bela Mbak?”
Dalam ngeri, Sita beradu pandang dengan Pak Basuki. Pria itu tampak nyaman-nyaman saja wajahnya dibenamkan ke buah dada Sita; yang tentu saja adalah berita buruk bagi si menantu.
“Pak Basuki?” Dengan santai Pak Reksha mengarahkan kontolnya ke lobang di tengah lipatan memek berlendir Sita tanpa bantuan tangannya. “Bapak saya kasih pilihan. Pilihan pertama, Bapak jadi saksinya Mbak Sita. Atau… pilihan kedua: Bapak ikut kita garap Mbak Sita. Hm? Ayo. Pilih mana?”
Sita menahan napasnya.
~bersambung
“Ayo, Pak.” Pak Reksha yang sempat melihat kemaluan Pak Basuki dari resleting celana yang terbuka. Tentunya, dia sendiri yang membukanya? “Kalau yang pertama, Bapak akan—”
“Hoher hua!” gumam Pak Basuki cepat.
Hancur sudah harapan Sita beserta sedikit segan dan hormat yang dia punya pada mertuanya. Hampir-hampir dia tidak terkejut saat pria itu kemudian mulai mengemut pentilnya. Sesuatu baru saja mati di dalam dirinya.
“Hahahahahahaha. Pinter juga Bapak! Sudah, Sir. Biar dia nyusu ke Mbak Sita.”
Tanpa jemari Basir di sekeliling lehernya, Pak Basuki bisa dengan leluasa memangsa buah dada Sita. Berpindah-pindah dia dari yang kiri. Ke yang kanan. Dan sebaliknya.
“Lepas tangannya Mbaknya juga, Sir.”
Basir memandangi ayahnya beberapa detik lamanya.
“Ndak papa. Sudah jinak, kok, ini.”
Demi membuktikan kata-katanya, Pak Reksha kandaskan penisnya ke dasar rahim Sita dalam satu hentakan. Sita pun mengaduh, lalu mendesah, dan … menerima. Begitu pun saat Pak Reksha mulai menggenjotnya dalam tempo sedang. Pinggul wanita itu… mengimbangi gerak mekanis kontol yang sedang mengaduk-aduk memeknya.
Melihatnya, Basir pun tidak punya pilihan selain patuh. Sesaat sesudah kedua tangan Sita bebas dan si empunya hanya memakai mereka untuk mencengkeram tepian kasur, Basir kembali memandangi ayahnya; meminta arahan.
Pak Reksha hindari tatapan Basir bukan karena sengaja. Dia hanya sedang ingin berkonsentrasi menyetubuhi Sita. Pada satu titik dia bahkan meminta Pak Basuki menyingkir agar dia bisa memiliki Sita untuk dirinya sendiri. Kata dia pada dua lelaki lain di ruangan sesudah dia gencet badan Sita, “Jangan ada yang ganggu.”
Menjilati air mata Sita, Pak Reksha berbisik lembut, “Saya senang Mbak sekarang paham. Mbak ndak lagi saya perkosa. Diperkosa itu kalau Mbaknya ngelawan. Kalau Mbak ndak suka. Solusi biar Mbak ndak diperkosa apa? Ya, jangan ngelawan. Gampang, kan?”
Seakan terbius kata-kata Pak Reksha, Sita kaitkan kaki-kaki jenjangnya di belakang pantat Pak Reksha. Sembari menangis menganak samudera, dia dekap laki-laki di atasnya. Saat Pak Reksha belum kembali menggenjotnya, dia bahkan mengambil inisiatif menggerakkan pinggulnya. Dia bimbing kontol di dalam memeknya dalam satu irama. Keberadaan Pak Basuki dan Basir yang di kanan dan kiri ranjang tidak mengganggunya.
Justru sebaliknya, ditonton oleh mata-mata lapar mereka, Sita jadi semakin lupa daratan. Semakin menyerah pada keadaan. Semakin dikuasai nafsu hewan.
Kata-kata Pak Reksha berhasil meracuni sisa akal sehatnya.
“Plookk… Plokkkk.. plokkk… Plokkkk”
“Plokkk… plokkk… plokkkkkkkk….”
Suara tumbukan kelamin mereka Sita rayakan belaka. Dia menjerit saat telinganya digigit-gigit. Dia mengaduh saat dasar rahimnya disundul-sundul. Dia mendesah saat balon-balon di dadanya yang bergoyang-goyang diremas-remas kasar. Dia melenguh saat otot-otot vaginanya melemas dan menegang seiring setiap genjotan. Dia memekik saat ketikanya dijiliat-jilat. Kepalanya yang masih terbungkus hijab menggeleng-geleng. Matanya mendelik-delik. Hidungnya kembang-kempis. Dia benamkan kuku-kuku jari tangannya pada punggung penjantannya.
“Uuugghh…. aaaaaah….. eeeghhhhh…. aaahhh… yyyyahhhhh….”
“Plookk… Plokkkk.. plokkk… Plokkkk”
“Huuuhhhh…. hhhaaaahhh…. huuuuhhhh….: aaaauuuuuuhhh….”
“Plookk… Plokkkk.. plokkk… Plokkkk”
“Plookk… Plokkkk.. plokkk… Plokkkk”
“Haaaaaahhhhh….. Uuuuuhh…. Eeeeeeeehhhmmmmmppphhhh….. Kyyaaaaa…….”
Dan sekali lagi, Sita mendaki hingga ke puncaknya. Deras cairan kewanitaannya mengguyur batang Pak Reksha. Sengaja laki-laki itu diamkan kontolnya demi memberi jeda baik bagi Sita maupun dirinya. Merem-melek dia keenakan. Kemaluannya serasa diurut, dipijat, diremas, diisap, dan dipelintir sekaligus. Tak mampu dia berkata-kata selama beberapa lama.
Sita sendiri merasakan kenikmatan yang tak terkira. Tulang-tulangnya serasa dilolosi. Sekujur badannya bergetar-getar. Otot-ototnya mengejang. Matanya berkunang-kunang. Sukmanya terbang. Tinggi melayang-layang. Kenikmatan itu datang dalam gelombang. Bertubi-tubi menendang.
Perlu dua menit lamanya sebelum Sita kembali sadar dia ada di mana dan sedang apa. Sempat terlintas sosok suaminya dalam pikirannya. Berikut juga ajaran-ajaran agama. Betapa jauh dia sudah terjatuh. Betapa kotor dia sekarang. Betapa berat dosa yang sudah dia catatakan. Meski demikian, saat kemudian Pak Reksha memagut bibirnya mesra lalu meminta lebih, dia serta merta menyanggupi. Sesal itu masih ada. Namun jauh sudah tenggelam dia dalam malam.
Dengan dibantu Pak Basuki dan Basir, dia tanggalkan celana dalam serta gamisnya. Berliter-liter keringat yang mengalir dari pori-pori membuat tubuhnya berkilat-kilat. Di bawah sinar lampu kamar, wajahnya yang penuh peluh tampak sepuluh tahun lebih muda. Kerutan di bawah matanya sirna. Seakan-akan dia baru saja dilahirkan kembali ke dunia.
Sita kemudian meraih penutup kepala. Akan tetapi, Pak Reksha mencegahnya.
“Jangan dilepas, Mbak.”
“Kenapa?”
“Mbak lebih cantik kalau jilbaban.”
“Saya… cantik di mata Bapak?”
“Oh, ya. Jelas.”
“Cantikan mana? Saya, atau istri-istrinya Bapak?”
“Hmmmm….”
Sita terkikik, mendesah, lalu menggeser lutut-lututnya hingga dia bersujud membelakangi Pak Reksha. Sedikit malu mengiringi kesuka relaannya mempertontonkan lebih banyak auratnya.
“Gini, kan, Pak?”
“Naik lagi bokongnya, Mbak.”
“Segini?” tanya Sita seperti pelacur murahan.
“Ya.” Takjub Pak Reksha melihat betapa simetrinya bulatan pantat bahenol Sita. Baik yang kanan maupun yang kiri sama-sama sekalnya. Sama-sama kenyal. Sama-sama sintal. Mulus lus lus luuus. Lobang mataharinya pun bersih. Jernih. Dan di bawahnya, Pak Reksha bisa melihat lipatan vagina yang mungil tengil. Di kanan dan kiri beliau, Pak Basuki dan Basir terhipnotis pemandangan yang sama. Takjub mereka. Dan terkhusus mertua Sita, pria tua itu bangga akan pilihan anaknya.
“Lagi,” kata Pak Reksha sambil mengelus permukaan bokong Sita. “Dikit lagi, Mbak.”
“Segini???”
“T-tangan,” kata Pak Reksha, maju dan bersiap di belakang kuda binalnya, “sama kepalanya naik dikit, Mbak. Yah. Nah, gitu. Bagus. Pinter.”
“Ayooo, Paak,” rengek Sita saat Pak Reksha menggodanya dengan meremas-remas teteknya yang berlegantungan manja. Agaknya lelaki itu sengaja berlama-lama mencoblos memeknya.
“Buru-buru mau ke mana to, Mbak?”
Saat kecupan Pak Reksha mendarat di tengkuknya, dia berkata, “Itu, lhooo, masukin lagi….”
“Apanya, Mbak?” tanya Pak Reksha di telinga Sita.
“P-penis Bapak!”
“Penis apa, Mbak?”
Pak Reksha masih berpura-pura ******. Sita yang sudah kepalang tanggung pun mulai menggoyang-goyangkan pantat bahenolnya.
“Itu, lho, burungnya Bapakkkk.”
“Ohhhh. Ini. Ini namanya kontol, Mbak.” Pak Reksha tersenyum jahil. “Coba, deh, Mbak Sita bilang.”
“Bilang apaah?”
“K-o-n-t-o-l, Mbak,” kata Pak Reksha dengan kesabaran seorang guru mengajari muridnya membaca.
“K-kontol?”
“Yang keras.”
“Koooontooool!”
“Pinter.” Pak Reksha tertawa, lalu meluruskan kembali punggungnya. Dia tekankan jari menuruni garis punggung hingga ke belahan pantat Sita yang dia akhiri dengan meremas-remas memek si wanita. “Kalau yang ini, apa namanya, Mbak?”
“Ihhh… hmpppp… tuuu, va-va-gina, Pakkkk….”
“Vagina? Salah, Mbak. Ini namanya tempik.”
“Iyaaahhhh….”
“Mbak mau tempiknya dijebol kontol?”
“Hehheeemmmmm….”
Pak Reksha menjepit itil Sita di antara ibu jari dan telunjuknya.
“Bilang Mbak.”
“Bilang apaaa lagiiii…..”
“Bilang ‘Pak, kontoli tempik saya’.”
Bagai kerbau dicokok hidungnya, Sita mengerang, “Paaakkkk… kontoli tempik saya….”
“Tambah ‘tolong’ di depannya kontol, dong.”
“PAAAAK, TOLOONG KONTOLIII TEMPIKK SAYAAA….”
Puas melecehkan Sita yang tadi Sore masih alim dan taat agama, Pak Reksha pun melesakkan kontolnya sedalam mungkin ke lobang tempik pelacur barunya. Dan tanpa membuang waktu, dia lalu memacu kuda betina itu. Bergoyang-goyang buah dada Sita dibuatnya. Maju-mundur. Maju-mundur. Maju-mundur.
Mula-mulanya, Pak Reksha memegangi pinggul Sita yang mentul-mentul. Setelah mereka bergerak seirama, dia raih satu tangan si akhwat. Dia tarik tangan itu hingga Pak Basuki yang berdiri di sebelah kiri Sita mendapat pemandangan ekskusif betapa menggairahkannya payudara menantunya. Lebih dari apapun juga, ingin dia menjamah balon nakal itu. Iri dia pada Pak Reksha yang begitu leluasa menggauli menantunya sementara dia hanya bisa menyaksikan sambil coli. Mana kontolnya lebih kecil dibanding milik dua lelaki lain yang satu ruangan dengannya pula.
Sumpah. Demi tuhan. Bunyi pantat bulat Sita yang membentur perut serta paha berlemak Pak Reksha membuatnya hampir gila.
“Plookk… Plokkkk.. plokkk… Plokkkk”
“Plookk… Plokkkk.. plokkk… Plokkkk”
“Plookk… Plokkkk.. plokkk… Plokkkk”
“Plookk… Plokkkk.. plokkk… Plokkkk”
“Yaaah… yaaahhhh…. entooot sayaaaa, Paaakkkkk….” racau Sita tanpa ada yang mengajari.
Tanpa memelankan laju aksi birahi, Pak Reksha melirik Pak Basuki lalu mengedipkan satu mata. Saat berbincang sebelum ruwat tadi, mereka sempat membahas usia perkwaninan Egi dan Sita yang sudah memasuki tahun ketujuh tapi belum juga dikarunai momongan. Sewaktu pasangan tersebut berkunjung di rumahnya, hal yang serupa pernah disinggung juga. Dia berkati mereka hanya dengan doa kala itu.
Baru ketika mengobrol dengan Pak Basuki Pak Reksha tahu seluruh kebenarannya. Menurut Pak Basuki, mereka pernah periksa ke dokter kandungan. Katanya, tidak ada yang salah dengan Sita. Adalah Egi yang gagal menjalankan tugasnya. Fakta itu kemudian ikut melandasi keputusan mereka bertolak ke desa. Konon, kualitas sperma Egi sukar membaik karena tingginya tingkat stress akibat hidup di ibukota.
“Plookk… Plokkkk.. plokkk… Plokkkk”
“Aaahhhh… Mbaaakkk…. saya…. mau….. nyammmmpeee….”
“Uuuuhhh…. saaayaaa…. aaahhhhh… juuggga paaakkk….”
“Di.. dalam… apa… di … luar?”
Sita yang kewalahan menggeleng seraya berkata, “ ‘serah Bapaaakkkk ajaa….”
“Mbakk maauuhh sayaa hhammiliii?”
“Maaauuuu…..”
Mendapat lampu ijo langsung dari yang bersangkutan, Pak Reksha meraih tangan Sita yang lain. Dia hentakkan kontolnya sekeras yang dia bisa hingga Sita merintih seperti anak kucing dibuatnya. Ketika orgasme itu datang, Pak Reksha tarik tangan-tangan Sita hingga melengkung seperti busur panah punggungnya. Bermili-mili sperma dia tembakkan ke rahim si akhwat. Mereka berteriak panjang bersama. Sepasang mata si kuda bahkan hingga berbalik ke dalam soketnya hingga yang tampak hanya putihnya.
Tontonan yang maha menggoda itu membuat Pak Basuki ejakulasi juga. Sementara Pak Reksha dan Sita ambruk ke depan saling bertindihan, Pak Basuki ambruk ke lantai. Dari seberang ranjang dia dapati Basir memandangnya jijik. Tak ada yang bisa dia lakukan selain membuang muka.
“Mbak?” tanya Pak Reksha di telinga Sita. “Masih mau lagi?”
“Ehhmmpp?”
Tanpa menunggu tanggapan selanjutnya, Pak Reksha cabut kontolnya. Pelan, memek Sita berhenti menggembung. Terlihat dari lobangnya lelehan kental sperma.
Merasa ada yang hilang, Sita merengek dengan mata yang masih terpejam, “Paakkk—Aaaahhh!”
Dari terpejam, Sita seketika mendelik. Mulutnya terbuka. Bibirnya membentuk huruf O besar. Sesuatu yang jauh lebih besar dari kontol Pak Reksha baru saja memasuki tempiknya. Dan berita buruknya, dia masuk begitu saja. Tidak ada permisi. Tidak ada ancang-ancang.
Memang, tempik Sita sudah melonggar. Tapi, tetap saja. Kontol yang baru ini kelewat besar! Rasanya seperti diperawani untuk yang ketiga kali. Sperma Pak Reksha yang tertampung dalam memeknya hanya sedikit meringankan sakit yang dia derita.
Melirik ke belakang, Sita dapati Basir-lah yang kini menggagahi. Basir si raksasa. Basir si anak haram Pak Reksha. Basir yang matanya selalu jelalatan menelanjanginya. Basir yang tadi hampir berhasil merontokkan giginya. Yang kontolnya tak bersunatnya sudah dia telan. Yang kantung kemih baunya menampar-nampar dagunya. Yang perut kotak-kotaknya ingin Sita raba.
Belum juga Sita sempat berkomentar apa-apa, pria itu sudah menggenjotnya. Keras. Kasar. Kejam. Membabi buta. Bahkan untuk mendongak dia tak kuasa. Seluruh bobot tubuhnya kini bertumpu ke kepala dan dada. Benar saja. Sekejap kemudian, lututnya mengudara.
Jika sebelumnya Pak Reksha menungganginya bagai kuda, Basir kini menggempurnya bak pelacur paling mujur. Setiap saraf di dalam tempik Sita menjerit gembira. Hasilnya, akhwat itu pun melolong bahagia.
“Splookk… splokkkk.. splokkk… splokkkk….”
“Uuuuuhhhggggg…. Uuuuuuuhhhhh…..”
“Splookk… splokkk…. splokkkk.. splokkk…. splokkkk”
“Uhhh… Uhhh…. Aaaauuuhhhhh….”
“Splookk… splokkkk.. splokkk…”
“Uhhhh… Ohhhk…. uhhhhh…… uhhhh……. ohhkkkkk…. ugghhhhhh….”
“Splookk… splokkkk….. Splokkkk…. ”
“Aaaahhhkk…. aaauuuuccchhh…. Uhhhhh…”
“Splookk… splokkkkss.. splokkk… Splokkkkss…”
“Uhhhkkk… Agggghh…. Uummmhhhhh….
Aaaauuuhhhhh….”
~bersambung
Kerasnya lolongan Sita bukan hanya terdengar sampai kamar sebelah namun juga menembus alam mimpi Egi.
Laki-laki itu tadinya sedang bermimpi buruk. Dari horison ke horison, yang dia lihat hanya petak-petak dan pematang-pematang sawah yang kosong. Langit mendung menggantung hanya beberapa jengkal dari kepalanya. Meski belum terdengar gemuruh, dia tahu akan adanya bahaya. Terutama, ketika dia sedang sibuk berkutat membebaskan Sita, istrinya—yang entah karena alasan apa telanjang bulat—yang tengah terjebak lumpur hitam di salah satu petak.
Lumpur itu dengan cepat mengisapnya. Mulanya dari mata kaki. Lalu naik ke lutut. Ke pinggang. Hingga ke dada. Panik, Egi yang aman di pematang sempat berniat untuk ikut terjun ke lumpur. Biar kalau Sita tidak selamat; dia juga. Namun, entah mengapa, hingga ubun-ubun istrinya karam, dia belum bergerak dari tempatnya.
Betapa pengecutnya dia.
Egi tidak punya waktu merutuki ketololannya, sebab tiba-tiba dia bisa mendengar lolongan yang menyayat telinga. Bukan. Lolongan itu bukan dari lumpur. Egi pun mendongak. Mendadak, seberkas cahaya menyambarnya.
Duar!
Egi pun terbangun di ranjang ayahnya. Lampu masih menyala. Tapi tidak ada siapa-siapa. Egi coba menelan ludah tapi tidak bisa. Dan berita buruknya, dia kembali mendengar lolongan Sita. Lebih lantang dari sebelumnya. Lebih keras. Lebih menderita.
Menderita?
Tunggu dulu.
Dalam keadaan ragu, Egi meraba-raba tepian kasur. Tangannya terasa berat. Kaki-kakinya seperti habis berlari maraton. Dan yang paling parah, kepalanya berdengung menyakitkan. Seolah sedang ada segerombol tawon pemarah di dalam sana. Semakin dia coba menggebah, semakin murka mereka. Pandangannya berkabut.
The very next thing he knows, Egi terjerembap dari kasur. Ya, dia terjatuh. Muka menghantam lantai lebih dulu. Dan selagi dia tertatih memungut dirinya sendiri dari lantai, lolongan dan erangan Sita menjadi musik pengiringnya.
Sesudah detik-detik yang terasa selamanya berlalu, Egi berhasil merangkak ke pintu. Sukses ini menyemangatinya. Dia gertakkan gigi dan meraih kusen. Dia seret tubuhnya bangun. Keringat membanjir dari seluruh pori-pori tubuhnya.
Pandangannya menggelap saat dia mencoba melepaskan tumpuan pada kusen dan percaya pada kaki-kakinya. Jika memaksakan diri berjalan normal, dia tahu dia hanya akan bertahan tiga langkah paling banter. Jadilah dia kemudian berjalan macam pemabuk yang habis minum segalon minuman keras hanya untuk lalu dia muntahkan lebih dari separuhnya. Jarak dari kamar ayahnya ke kamarnya sendiri yang hanya beberapa jangkah terasa seperti tidak ada habisnya.
Entah bagaimana, Egi tiba juga di depan pintu yang tertutup. Dia bisa melihatnya. Dia ulurkan tangannya. Dia bisa meraihnya.
Dan dia meleset.
Hanya udara yang Egi genggam. Keseimbangan tubuhnya yang sedang bercanda memperparah kegagalannya. Kakinya yang sekokoh agar-agar menyerah di bawah beban dan momentum yang tercipta.
Dia terjatuh lagi.
Egi butuh waktu lebih lama memungut dirinya kali ini. Bukan saja karena dia mulai bisa menebak apa yang terjadi di balik pintu, yang terjadi pada istrinya, namun juga karena dia kehabisan tenaga. Kehabisan napas. Ada kira-kira tiga menit dia telungkup di depan kamarnya.
Merasa sedikit lebih kuat, Egi dorong tubuhnya untuk duduk. Untuk bersandar pada daun pintu. Dia tempelkan telinganya ke lembar kayu. Ya. Tidak salah lagi. Istrinya pasti sedang….
Egi menggeleng. Tidak. Tidak. Tidak. Dia harus melihatnya dulu. Dia harus pastikan imajinasi liar di kepalanya punya bukti. Punya landasan.
Menggeram, Egi kembali meraih gagang pintu. Kali ini, dia berhasil. Dia putar gagang itu. Menurut gagang itu. Dia tinggal mendorongnya membu—
Tunggu dulu.
Egi membeku.
Dari lobang kunci, dia bisa melihat ke dalam. Samar awalnya. Dia juga sedang tidak mengenakan kacamatanya. Namun, dia bisa melihat siluet-siluet tubuh manusia. Mereka… telanjang?
Salah satu dari mereka… wanita.
Istrinya.
Sita.
Egi tidak percaya, awalnya. Tetapi, lama-lama dia yakin juga itu istrinya. Dia kenal tubuh itu. Dia kenal hijab itu. Dan yang di belakangnya…. Basir! Mereka sedang… bersetubuh… di depan.. meja rias. Sita merunduk seperti orang rukuk yang jauh dari khusyuk. Dia terdorong-dorong sampai kakinya terjinjit-jinjit. Jika bukan karena jemari yang mencengkeram tepian meja, sudah pasti dia akan terhempas ke depan. Menabrak cermin di depannya. Buah dadanya terpental-pental seperti hendak meloncat ke meja.
Sedikit pun tak menunjukkan pengertian, laki-laki dibelakangnya terus saja memompa apa yang di mata Egi terlihat seperti penis kuda. Hitam dan panjang. Setiap sodokan lebih kencang dari yang sebelumnya. Lebih bertenaga. Dari pertemuan kelamin mereka dia mendengar bunyi “plok-plok-plok” yang mengingatkannya pada bunyi petani mencangkul tanah basah.
Dan omong-omong soal basah, baik Basir maupun Sita dia lihat sama-sama bermandikan peluh. Kulit mereka berkilat. Kontras sekali beda kulit keduanya. Yang satu kuning langsat cenderung putih hangat. Yang satunya lagi hitam laknat.
Mulanya Egi merasa mual menonton adegan itu. Namun, segera mual itu menguap saat dia dapati betapa menikmatinya Sita. Betapa berbeda wanita itu kedengarannya jika dibandingkan dengan saat bercinta dengannya.
Sebelum dia bisa betul-betul mencerna emosinya sendiri, Egi rasakan celananya menggembung.
Kemaluannya berdiri.
Keras.
Persetan, batin Egi sebelum mengeluarkan alat kelaminnya lalu mulai coli. Kembali dia tonton istrinya digauli.
“Yes. Yes…. Ohkk… Fuckkk… Yesss….” rintih Sita saat Basir menaikkan satu kakinya ke meja. Sakit yang dia terima terasa 110% sepadan dengan nikmat yang dia terima. Setiap kali kontol Basir menggaruk relung tempiknya, Sita yakin tempurung lututnya hendak meletus. Bisa dia rasakan mulut vaginanya monyong-melesak seiring genjotan demi genjotan.
And yet…. Sita ingin lebih. Dia tak ingin Basir berhenti. Dia ingin nikmat itu abadi.
“Enak mana, Mbak?” tanya Pak Reksha yang kini duduk di pinggiran kasur sambil merokok pipa. Bersama Pak Basuki yang menggelesot di lantai sambil menunggu burungnya kembali bangun dia saksikan bagaimana Sita dilumat anak haramnya. Diawali di atas kasur, lalu di lantai, sebelum berpindah ke depan meja. Setengah jam sudah berlalu sejak kelamin mereka bertemu. Dan belum tampak lelah pada diri raksasa itu.
Dalam kekuasaan Basir, wanita berjilbab itu tak ubahnya seonggok daging mentah. Sebuah boneka pemuas nafsu semata. Tanpa hijab panjang di kepala yang menutup hingga ke dada, Sita akan sempurna tampak bagaikan sesosok pelacur nista yang tidak peduli dengan bayaran, tidak menggubris kemungkinan besok tidak akan lagi bisa berjalan, tidak peduli isi perutnya terburai diaduk sedemikian rupa asalkan dia terus-terusan dihajar oleh sang pejantannya.
“Enak mana, Mbak? Kontol kita atau kontol suamimu tercinta?”
Sita tangkap pertanyaan Pak Reksha. Akan tetapi, dia terlalu larut dimabuk kepayang. Mata sayunya hanya setengah terbuka. Bayangan dirinya dientot dalam posisi anjing kawin memandangnya balik. Segumpal helai rambut lolos dari hijabnya yang mawut dan berjatuhan di dahinya.
Di satu momen, Sita curiga bayangan itu menertawakannya. Mengejek betapa polos dulunya dia. Jika sekarang suaminya menyaksikan dirinya, Sita bersumpah dia akan membunuh argumen Egi yang pernah menyebut kenikmatan yang dijual dalam video-video bokep itu tidak ada. Hanya dibuat-buat semata. Tengok saja dia sekarang. Apanya yang dibuat-buat? Tidak ada. Semuanya real. Dia sedang menyelami saripati bercinta. Dia sedang memahami makna sebenarnya menjadi seorang wanita.
Jika Basir semabuk Sita, pria itu tak menunjukkannya. Terbukti, pertanyaan ayahnya barusan mengendap di telinganya. Pasca menusuk jauh-jauh rahim Sita hingga betina itu klimaks untuk kali kelima malam itu, dia hentikan hentakkannya. Kasar dia jambak ekor jilbab Sita. Menggeram, dia suruh betina itu menjawab.
“Ehhh,” erang Sita lemah, “nahk punya kalian.”
Basir menyeringai. Dia pandangi sosoknya pada pantulan kaca. Betapa kerdil sosok Sita yang tak berdaya di depannya. Selagi ayahnya terkekeh di belakangnya, dia ayunkan lagi kontolnya. Kecipak persenggamaan mereka kembali mengudara.
Lalu, tanpa aba-aba, dia lepaskan tangannya dari jilbab Sita. Tangan-tangan kemudian menjamah bagian belakang paha. Kaki yang dia turunkan dari meja sekarang berpijak perkasa. Tanpa memelankan genjotan, dia gendong Sita.
Berlama-lama dia suguhi Sita pemandangan di cermin setinggi tujuh puluh centimeter itu. Dia ingin betinanya tidak akan pernah lupa siapa juaranya malam itu. Dia ingin Sita mengenang malam itu selamanya.
Sementara Sita sedang dalam perjalanannya menggapai orgasme berikutnya, Egi yang ejakulasi setengah menit sejak dia mulai coli gagal mengalihkan tatapan dari istrinya. Dari gerakan memompa si raksasa. Dari guncangan kepala berjilbab Sita. Lima belas menit sesudahnya, istrinya tampak akan mencapai batasnya. Menggelepar akhwat itu dalam gendongan si laki-laki bar-bar. Dan untuk kali ini, lawan main Sita sepertinya juga sudah ingin memuntahkan lahar panasnya.
Dugaan Egi mewujud realita. Diiringi teriakan kesetanan, Basir empaskan pantat Sita ke kontolnya. Pada saat yang sama, Egi cekik burung pipitnya. Sejurus kemudian, kelamin mereka berpisah.
Ploooppp!
Egi mendapati dari lobang menganga di tubuh Sita, deras mengucur cairan kental sperma.
Banyak sekali!
Berapa kali Sita sudah disetubuhi?
Mustahil baru sekali tentunya!
Pikiran-pikiran ini melumpuhkan Egi. Lututnya menolak menopang tubuhnya lebih lama lagi. Dengan satu sisi badan menggelesot di lantai, dia terisak tanpa suara.
~bersambung
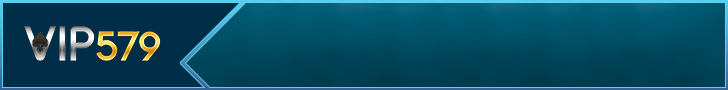
.gif)














